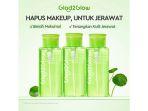Berita Sukoharjo Terbaru
Cerita Tentang Surya Hastono, Juru Kunci Keraton Kartasura, Dapat Gaji Rp 107 Ribu per Bulan
Menjadi abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta menjadi kebanggaan tersendiri bagi sejumlah masyarakat.Seperti Surya Hastono Hadi Projo.
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Ryantono Puji Santoso
Memang tidak banyak yang bisa dilihat di bekas kerajaan besar itu, selain ribuan makam yang terawat maupun yang sudah tak pernah dipelihara lagi.
Selain lubang di benteng Srimanganti, jejak Keraton Kartasura lain adalah titik lokasi bekas kamar tidur raja.
Lokasi itu ditandai sebuah paseban terbuka yang fisik bangunannya belum terlalu lama. Di paseban itu ada dua batu besar berselimut kain ungu, sebagai penanda bekas kamar raja.
Ada pohon beringin besar menaungi spot ini. "Katanya sih ini lokasi paling wingit, dijaga ular besar, tapi hanya orang tertentu yang bisa melihatnya," jelas Freddo.
Beberapa waktu lalu di lokasi ini, digunakan untuk rekaman mata acara uji nyali oleh sebuah stasiun televisi.
"Nggak ada yang kuat, semua peserta angkat tangan ketakutan," lanjut lulusan sebuah sekolah komputer di Solo ini.
Komplek Keraton Kartasura sesungguhnya sangat luas pada masa jayanya. Tata letaknya persis seperti yang sekarang bisa dilihat di Keraton Kasultanan Yogya maupun Kasunanan Solo.
Benteng terluarnya yang sangat tinggi, sekitar empat meter tingginya, masih bisa dilihat sisanya di sebelah barat, sekitar 200 meter dari gerbang belakang cepuri.
Sisa tembok baluwarti itu memanjang sekitar 60 meter, bersisian dengan jalan sisi barat Kampung Sitihinggil.
Kondisinya di beberapa bagian rapuh, miring dan melesak di sana-sini, serta ditumbuhi rumput liar dan semak belukar.
Dari toponimi yang dikenal sekarang, tata letak komplek Keraton Kartasura membujur arah selatan utara.
Dimulai dari Alun-alun Utara yang saat ini berubah jadi permukiman dan pertokoan. Letaknya di utara pertigaan Jalan Kartasura-Pajang, atau utara komplek sekolah Muhammadiyah.
Berikutnya di selatan alun-alun adalah Pagelaran Keraton yang lokasinya kini jadi Kampung Pagelaran.
Berikutnya di selatan adalah komplek Sitihinggil Keraton, yang kini jadi Kampung Sitihinggil. Di selatan Sitihinggil ini ada bekas bangsal Srimanganti yang jadi penghubung ke cepuri atau tempat tinggal raja.
Keluar dari cepuri ini di sebelah selatan masih ada area lain sebelum mencapai tembok baluwarti dan Alun-alun Selatan. Semua area ini sekarang sudah jadi perkampungan masyarakat.
Harta Kerajaan Gagal Dibawa Lari
Seorang bangsawan Keraton Surakarta, Daradjadi, secara apik menuliskan kisah dramatis perang yang meruntuhkan Keraton Kartasura pada 1742.
Dalam buku Geger Pacinan 1740-1743 (Penerbit Kompas, 2013), peristiwa berdarah itu dikenang sebagai "Geger Pacinan", seperti judul bukunya.
Mengapa Geger Pacinan? Penyerbuan ke Keraton Kartasura yang kala itu dikuasai Sunan Pakubuwana II, sesungguhnya tidak berdiri sebagai konflik sendiri.
Peristiwa itu berkelindan dengan pemberontakan etnis Tionghoa di Batavia, yang akhirnya dibantai secara kejam oleh pasukan VOC pada 10 Oktober 1740.
Tokoh-tokoh radikal etnis Tionghoa di Batavia yang memimpin pemberontakan melarikan diri ke timur, melanjutkan perlawanan di Jawa Tengah.
Mereka yang jumlahnya ribuan, bergabung dengan kelompok bangsawan Mataram, yang hendak mendongkel Sunan Pakubuwana II karena bersekutu dengan VOC.
Sejumlah bangsawan Mataram itu mengangkat Raden Mas Garendi, cucu Sunan Amangkurat III yang baru berumur 12 tahun, sebagai Sunan Amangkurat V.
Datanglah bocah belia itu ke Kartasura, memimpin balatentara campuran Tionghoa dan Jawa yang kemudian menghancurleburkan pusat kerajaan Mataram yang dijaga kompeni.
Karena memimpin pasukan Tionghoa itulah, Raden Mas Garendi atau Sunan Amangkurat V ini juga dikenal sebagai Sunan Kuning.
Dalam bukunya, Daradjadi melukiskan detik-detik ketika pasukan penyerbu yang saat itu dikomandani Kapiten Sepanjang menggempur keraton.
Kapten Baron van Hohendorff adalah komandan garnisun VOC yang mendirikan benteng di luar Keraton Kartasura saat serangan terjadi.
Ketika Kapiten Sepanjang dan pasukannya merangsek masuk ke Pagelaran dan Sitihinggil, Hooendorff sudah bergabung dengan Sunan Pakubuwana II di cepuri keraton.
Ia menyaksikan raja itu berdiri mematung di tengah suasana panik, sembari menggenggam tombak.
Di luar benteng, suara riuh rendah tembakan terdengar berselang-seling suara tambur, perkusi dan teriakan para prajurit.
Hohendorff memerintahkan semua prajurit pengawal masuik cepuri dan mengunci pintu besar nan tebal yang menghubungkan area Sitihinggil dengan tempat tinggal raja.
Selanjutnya, usaha evakuasi dan penyelamatan dimulai lewat pintu belakang keraton. Ratu Amangkurat, atau ibu suri raja, berkali-kali pingsan dalam suasana kalut saat dipandu naik ke pelana kuda.
Ratusan prajurit, kerabat dalem berlarian ke belakang, berebut pintu keluar yang sempit. Banyak di antara mereka terluka oleh senjata sendiri, jatuh terinjak-injak di depan pintu.
Bergelimpangan di antara barang bawaan dan harta kerajaan, orang-orang yang pingsan atau meninggal itu semakin menghalangi usaha pelarian.
Para prajurit yang masih kuat, akhirnya memanjat tembok baluwarti. Namun mereka disongsong tembakan dan tusukan tombak para penyerbu yang ternyata mengepung pintu belakang.
Hohendorff dan sejumlah kecil prajuritnya serta komandan pengawal raja, Wirareja, membawa Sunan Pakubuwana II dan putra mahkota yang masih belia, mencari jalan lain di dinding sebelah timur.
Mereka menemukan lubang kecil seukuran badan, dan diam-diam akhirnya meloloskan raja ke daerah timur keraton yang tengah terbakar. Putranya terpisah karena terkena tembakan di dada.
Hohendorff dan Sunan Pakubuwana II berjalan kaki, meniti persawahan dan ladang hingga tiba di sebuah perkampungan dan menemukan seekor kuda.
Tujuannya menjauh ke timur ke arah Bengawan Solo. Wirareja semula menyarankan agar Hohendorff membawa Sunan ke Semarang.
Tapi permintaan ini ditolak, dan Hohendorff memutuskan akan membawa Raja ke seberang Bengawan Solo menuju daerah-daerah aman di bawah kekuasaan Mataram.
Sebelum menyeberang sungai, di daerah Laweyan, raja yang tersingkir itu istirahat, dan tiba-tiba di kejauhan ada rombongan datang membawa putra mahkota yang terluka.
Bocah itu digendong seorang prajurit yang loyal, sementara di belakang mereka terus mengejar balantentara Kapiten Sepanjang.
Bergegas rombongan kerajaan itu menyeberang Bengawan Solo, menuju ke Magetan lewat Karanganyar dan mendaki lereng selatan Gunung Lawu.
Mereka disusul sepasukan kecil prajurit setianya, dan ketika tiba di Magetan, Sunan Pakubuwana II mengirim pesan ke Bupati Madiun Adipati Mertalaya, apakah bersedia memberi perlindungan.
Selama enam hari, raja tinggal di Madiun, sebelum rombongan bergerak ke Ponorogo, di bawah perlindungan Bupati Surobroto yang dianggap lebih kuat dan loyal.
Di Keraton Kartasura yang hancur dan jadi tempat jarah rayah, pergolakan baru sedang bersemi. Tumbangnya Sunan Pakubuwana II membuat elite bangsawan Mataram berebut pengaruh dan kekuasaan.
Sunan Kuning atau Amangkurat V terlalu belia, dan ia hanya jadi simbol perlawanan belaka dari segelintir elite dan pasukan Tionghoa yang bergerilya di Jawa Tengah.
Raja Mataram yang sah sebetulnya masih ada, yaitu Sunan Pakubuwana II, yang berada di pengungsian Ponorogo.
Ia nanti akan kembali ke Keraton Kartasura, namun dalam keadaan yang sudah jauh berubah. Mataram yang tadinya besar, akan semakin berkeping.
Pasukan Madura Kuasai Istana
Keraton Kartasura jatuh pada 30 Juni 1742, Sunan Pakubuwana II melarikan diri ke Magetan, Madiun, sebelum berdiam di Ponorogo. Apa yang terjadi sesudah itu?
Berbagai literatur sejarah menyebutkan, peristiwa Geger Pacinan itu pada akhirnya memantik pertikaian di antara elite bangsawan Mataram.
Kerajaan besar itu akhirnya semakin terpuruk, sebelum akhirnya tunduk penuh di bawah kaki VOC.
Ketika Keraton Kartasura dikuasai Kapiten Sepanjang dan pasukannya, Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning atau Sunan Amangkurat V, tinggal berdiam memantau jalannya peperangan di daerah Ngasem (kemungkinan di bagian timur Boyolali).
Ada dua tokoh terkemuka Mataram yang ikut membantu Kapiten Sepanjang, dan masuk ke keratin yang porakporanda. Keduanya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said (Pangeran Suryokusumo).

Mangkubumi menemukan tombak pusaka Kyai Plered, sementara Raden Mas Said merampas keris pusaka Kyai Bedudak dari tangan prajurit Tionghoa.
Kedua benda itu dalam keyakinan Jawa saat itu bisa jadi simbol legitimasi penguasa.
Kelak memang, kedua tokoh itu akan jadi pemimpin dan pendiri trah dan wilayah kekuasaan sendiri.
Mangkubumi mendirikan Kasultanan Yogyakarta sebagai Hamengkubuwana I, sedangkan Raden Mas Said jadi pendiri praja Mangkunegaran.
Sehari sesudah Keraton Kartasura dikuasai, Kapiten Sepanjang menjemput Sunan Kuning ke Ngasem, dan kemudian mendudukkan bocah itu ke singgasana di Sitihinggil.
Mulai 1 Juli 1742, Sunan Amangkurat V memimpin sekaligus memantik pergolakan baru.
Ia didampingi Tumenggung Mangunoneng sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari.
Di tangan sang patih inilah, roda pemerintahan Keraton Kartasura dijalankan. Perang melawan kompeni berlanjut di berbagai tempat.
Kapiten Sepanjang meneruskan perlawanan di berbagai daerah, terutama pesisir utara Jawa bagian tengah.
Di sisi lain, VOC mencoba menarik keuntungan politik dan militer di tengah pergolakan internal bangsawan Mataram.
Di Madura, Adipati Cakraningrat IV juga bertindak melawan VOC sekaligus berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram.
Di Ponorogo, Sunan Pakubuwana II mempersiapkan usaha merebut kembali kekuasaan, dibantu para loyalisnya.
Sunan Kuning pada akhirnya harus menghadapi tiga front perlawanan, yang semuanya berusaha keras meruntuhkan kekuasaanya di Kartasura.
Pada 5 Agustus 1742, Sunan Pakubuwana II mengirimkan pasukan guna merebut Kartasura.
Serangan lewat daerah Nguter, Sukoharjo, itu gagal total.
Pasukannya dipukul mundur.
Sunan meminta bantuan Bupati Madiun, yang mengirim pasukan lewat Sukowati (Sragen). Lagi-lagi gelombang serangan ini dipukul mundur pasukan Sunan Kuning.
Sesudah kegagalan ini, Kapten Baron von Hohendorff meminta Sunan diam, tidak berusaha menyerang Kartasura, hingga VOC nanti siap member dukungan penuh guna merebut kembali kerajaannya.
Kapiten Sepanjang, Singseh, dan banyak pemimpin laskar Tionghoa, bergerilya di pesisir utara Jawa.
Mereka bertindak sendiri maupun kolaborasi dengan pengikut Sunan Kuning di berbagai daerah yang masih setia.
Persiapan besar kemudian dilakukan Hugo Verijsel dan Hohendorff di Semarang, sebagai pusat VOC di Jawa bagian tengah.
Mereka akan menggempur Kartasura lewat Salatiga. Di timur, Adipati Cakraningrat IV dari Madura juga menggelar persiapan yang sama.
Di Ponorogo, Sunan Pakubuwana II yang berganti nama Panembahan Brawijaya juga menyiapkan diri untuk gempuran pamungkas ke Kartasura.
Tanggal pertengahan November 1742, serangan dari tiga arah dan tiga kelompok berbeda dimulai.
Ini berarti lima bulan sesudah Keraton Kartasura jatuh. Raden Mas Garendi atau Amangkurat V digoyang dari tiga jurusan berbeda, dan ada tiga kelompok besar yang berbeda kepentingannya.
Adipati Madura ingin bebas dari cengkeraman VOC sekaligus lepas dari Mataram, sementara Pakubuwana II ingin merebut kembali tahta.
Sedangkan VOC berusaha menundukkan Sunan Kuning, menekuk lebih dalam lagi Mataram dalam pengaruh dan kekuasaan mereka.
Gelombang kedatangan penyerbu muncul dari arah Sukowati (Sragen) di sebelah timur Bengawan Solo.
Mereka terlibat bentrokan dengan pasukan Tumenggung Mangunoneng, sebelum mencapai tepi sungai.
Di lokasi ini mereka dicegat pasukan Tionghoa, yang berhasil mereka pukul mundur.
Saat mundur menyeberagi Bengawan Solo ini, pasukan Tionghoa yang dipimpin Pibulung dan Macan, banyak yang tewas ditembak dan hanyut ke hilir.
Sisa yang selamat lari ke Kartasura guna menyelamatkan Sunan Kuning.
Setiba di keraton, mereka membawa lari Sunan Kuning ke selatan.
Di saat yang sama, pasukan Madura tiba di keraton dan menduduki istana.
Hari itu tanggal 26 November 1742.
Pasukan VOC masih tertahan di Salatiga, sementara rombongan Pakubuwana II dari Ponorogo juga menyusul mendekat ke Kartasura.
Mereka tertahan di Gumpang, sebelah timur keraton.
Tentara Madura yang menguasai Keraton Kartasura menolak menyerahkan tahta ke Pakubuwana II.
Ini memaksa VOC turun tangan dengan segala cara, membujuk Adipati Cakraningrat IV supaya menyerahkan kedaulatan keraton.
Pada 9 Desember 1742, Residen Surabaya De Klerk menemui Cakraningrat IV yang marah, namun kemudian melunak dan bersedia mengosongkan Keraton Kartasura.
Ia menarik sebagian besar prajuritnya, dan menyisakan 300 serdadu hingga pasukan kompeni tiba.
Pada 20 Desember 1742, pasukan VOC di bawah komando Nathanel Steinmetz dan Von Hohendorff tiba di Kartasura dan memasuki keraton.
Keesokan harinya, atau 10 Desember 1742, Pakubuwana II diarak kembali masuk ke keratonnya yang rusak parah.
Ia ditahtakan kembali oleh kompeni. Sunan bertemu kembali dengan ibu suri, Ratu Amangkurat dan permaisurinya, Ratu Maduretno, yang bertahan di keraton setelah Sunan Kuning merebut Keraton Kartasura enam bulan sebelumnya.
Akhir Tragis Sunan Kuning
Pada 26 November 1742, lima bulan sesudah bertahta di Keraton Kartasura, Raden Mas Garendi atau Amangkurat V terusir dari istananya.
Saat pasukan Madura datang merebut keraton, Sunan Kuning melarikan diri ke selatan dikawal Tumenggung Mangunoneng, Pangeran Suryokusumo atau Raden Mas Said dan Kapiten Sepanjang.
Mereka membangun kubu di daerah Randulawang. Sekarang daerahnya di sekitar tepi Kali Opak, selatan Prambanan. Raden Mas Garendi yang masih belia, dan para sekutunya ini mempersiapkan kembali usaha merebut keraton.
Kekuatan pasukan mereka sekitar 900 orang saja. Pangeran Sambernyowo memimpin serangan balik, namun gagal menembus pertahanan keraton. Mereka dipukul mundur dan kehilangan banyak nyawa prajuritnya.
Sekali lagi, laskar Sunan Kuning berbalik menyerang keraton dari sisi lain, membakar pos kompeni di belakang paseban keraton. Kompeni mengerahkan pasukan Ternate dan Bugis, dan sukses menghancurkan sisa laskar Sunan Kuning di Dersono.
Musim hujan di awal tahun 1743 menyulitkan pergerakan pasukan Pakubuwana II dan VOC. Baru pada 3 Juni 1743, Hohendorff memimpin 1.000 prajurit VOC, guna menumpas Sunan Kuning di Randulawang.
Serangan hebat itu memecah belah pasukan Sunan Kuning yang lari ke timur menuju Wonogiri bersama Pangeran Sambernyowo. Sedangkan Tumenggung Mangunoneng larike barat menuju Bagelen (Purworejo), sebelum lari ke Tegal dan menyerahkan diri ke kompeni.
Usaha menyelamatkan diri sambil memberikan perlawanan dilakukan Sunan Kuning dan Raden Mas Said di Wonogiri, Ponorogo, Magetan, Caruban dan sekitarnya. Di titik ini, kemudian terjadi perbedaan pendapat.
Raden Mas Said ingin berjuang di sebelah timur Kartasura, tidak jauh dari tanah kelahirannya. Sementara Sunan Kuning dan Kapiten Sepanjang berusaha bergabung dengan kelompok Untung Surapati di Bangil, Pasuruan dan sekitar Surabaya.
Kapiten Sepanjang saat itu sudah tiga tahun bertempur dan bergerilya melawan pasukan VOC. Sejak dari Tangerang, Batavia, Cirebon, terus ke timur dari Pekalongan, Batang, Semarang, Kartasura, Demak, hingga Rembang.
Ia sudah kehilangan banyak prajurit Tionghoa, dan melihat wilayah timur punya potensi besar untuk menambah kekuatan. Keturunan Untung Surapati saat itu bersekutu dengan gerilyawan Tionghoa melawan kompeni.
Akhirnya, Raden Mas Said pamit tidak bersedia melanjutkan perjuangan di wilayah timur. Ia kembali ke barat, ke Sukawati (Sragen), bergabung dengan pasukan Singseh yang bergerak di Grobogan dan sekitarnya.
Sunan Kuning bersama Kapiten Sepanjang serta sisa pasukannya meninggalkan Caruban, menuju Kediri, sebelum melanjutkan perjalanan ke Pasuruan. Pada September 1743, laskar Sunan Kuning dan Kapiten Sepanjang memasuki selatan Surabaya.
Dalam sebuah pertempuran, Sunan Kuning terpisah dari Kapiten Sepanjang, namun lolos dari maut. Amangkurat V itu galau karena sisa kekuatannya sungguh sudah tidak mampu meladeni peperangan.
Pada 2 Desember 1743, Sunan Kuning dan rombongan akhirnya berarak menuju Loji Kompeni, tempat kediaman Residen Surabaya De Klerk.
Ia menyerahkan diri disertai para istrinya dan 300 prajuritnya.
Diduga Sunan Kuning memenuhi tawaran damai dari VOC. John Heinrich Schroeder, seorang prajurit VOC dari Prusia (Jerman), membuat kesaksian terkait penyerahan diri Sunan Kuning di Surabaya.
Schroeder menggambarkan pangeran itu datang membawa 50 istri dan selirnya serta 300 pengikut setia. Setelah beberapa hari ditahan di Surabaya, Sunan Kuning dibawa ke Semarang.
Di kota ini, para pengikutnya yang kebanyakan etnis Tionghoa dieksekusi mati.
Setelah itu Sunan Kuning dibawa ke Batavia, selanjutnya dibuang ke Ceylon (Srilangka), menyusul sejumlah pendahulunya.
Sunan Amangkurat V yang jadi raja Mataram hanya lima bulan, berada di pembuangan hingga akhir hayatnya.
Sementara Kapiten Sepanjang lari ke Blambangan (Banyuwangi) sembari menggempur pos-pos kompeni di sepanjang jalan.
Ia lolos dari sergapan pasukan VOC hingga akhirnya menyeberang ke Bali, dan mendapat perlindungan raja-raja di sana.
Kembalinya Sunan Pakubuwana II ke tahta Keraton Kartasura, bukan berarti memperbaiki keadaan secara politik. Justru peristiwa ini menjadi titik awal semakin kuatnya cengkeraman VOC atas tanah Jawa di bawah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff di Batavia.
Di tangan Van Imhoff lah, kemudian dilakukan usaha pembersihan semua yang berani melawan kompeni. Seorang penasehat Pakubuwana II, Sayed Aluwi, ulama berpengaruh, diciduk dari Kartasura dan dipenjarakan di Batavia.
Van Imhoff juga menentukan wilayah yang jadi kekuasaan Sunan Pakubuwana II. Madura dan Sidayu (Gresik) diserahkan ke kompeni. Pemimpin kedua daerah itu harus keturunan Adipati Cakraningrat IV.
Surabaya, Rembang, Jepara juga dikuasai VOC. Wilayah pesisir memang diserahkan ke Kartasura, namun praktis para penguasa wilayah itu ada di bawah kontrol kompeni. Semua pos bea cukai dikuasai penguasa kolonial.
Terakhir, Van Imhoff menentukan penentuan dan pengangkatan patih kerajaan harus sepersetujuan kompeni. Sunan Pakubuwana II yang tak berdaya, sama sekali tidak menolak proposal perjanjian ini.
Ini merupakan pukulan terakhir yang menjadi penanda runtuhnya kekuasaan Mataram, sejak didirikan di Kotagede oleh Panembahan Senopati pada 1577 Masehi. (*)